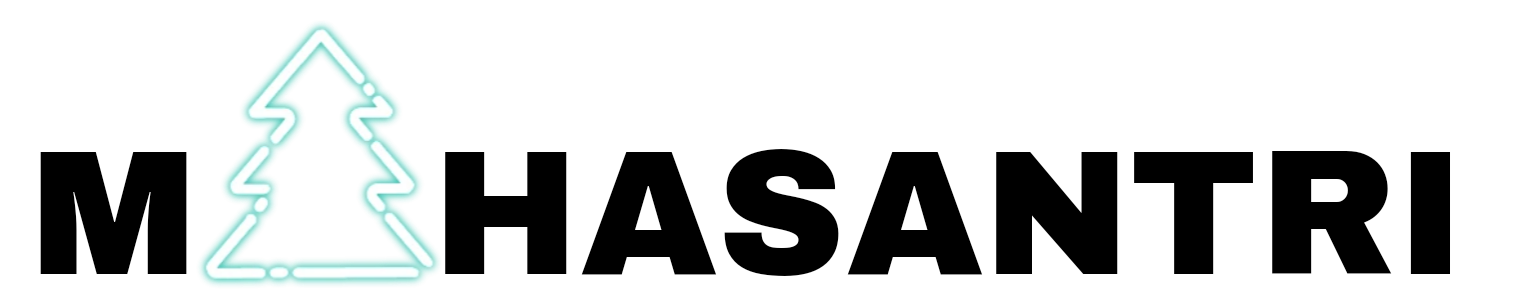Dari stoikisme, saya pernah belajar satu prinsip penting: kita tidak bisa mengendalikan persepsi atau opini orang lain terhadap kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Namun, tulisan kali ini ingin saya jauhkan dari sudut pandang stoik tersebut. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi yang lebih dalam, tentang bagaimana kurangnya dukungan dari orang terdekat bisa membuat hobi yang kita cintai terasa hampa.
Ada tiga kegiatan yang telah saya lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, dan saya benar-benar mencintai prosesnya: menulis, fotografi, serta olahraga angkat beban di gym. Semuanya saya jalani dengan sepenuh hati—menulis sebagai cara menuangkan pikiran dan emosi, fotografi untuk menangkap keindahan momen sehari-hari, dan gym sebagai disiplin untuk menjaga kesehatan jasmani. Dulu, kepuasan datang murni dari proses itu sendiri.
Namun, beberapa bulan belakangan, semuanya mulai terasa berbeda. Pengaruh media sosial membuat saya sering membandingkan diri dengan orang lain—melihat mereka mendapat likes berlimpah, komentar pujian, atau dukungan keluarga yang terbuka. Di sisi lain, saya justru tidak pernah benar-benar mendapatkan validasi positif dari keluarga maupun teman terdekat. Hasilnya, kegiatan yang dulu membahagiakan kini sering terasa kosong dan tak bermakna lagi.
Cerita kecil yang masih membekas hingga kini terjadi saat saya baru menjadi mahasiswa di Mesir. Ada tradisi dari senior kepada junior: kami diwajibkan membentuk tim majalah kampus yang akan diterbitkan saat wisuda. Banyak teman seangkatan yang juga suka menulis, tapi saya mungkin yang paling "tidak tahu diri" dalam mempromosikan tulisan sendiri—sering membagikannya kepada senior dengan harapan diakui. Namun, saat pengumuman anggota tim majalah, nama saya tidak tercantum. Remeh memang, tapi rasa kecewa itu lumayan membekas, seperti tamparan kecil bahwa usaha saya tidak dilihat.
Hal serupa berulang dengan orang tua. Saat mereka tahu saya suka menulis, respons awal justru larangan—mungkin khawatir itu mengganggu studi atau tidak "produktif". Baru setelah buku antologi kedua yang saya ikuti terbit, ayah dan ibu mulai sedikit mendukung, bahkan mendorong saya untuk terus menulis. Pola yang sama terjadi pada fotografi dan gym: jarang ada pujian, lebih sering pertanyaan skeptis seperti "Untuk apa capek-capek?" atau "Kapan hasilnya kelihatan?"
Saya tahu, banyak orang mengalami hal serupa. Anak-anak yang hobinya tidak didukung lingkungan terdekat sering merasa terisolasi. Contoh klasik adalah kisah banyak seniman atau atlet pemula yang awalnya dicibir keluarga, tapi kemudian berhasil karena tetap istiqomah. Misalnya, J.K. Rowling yang ditolak puluhan penerbit sebelum Harry Potter sukses, atau atlet Lionel Messi yang dianggap terlalu kecil untuk bermain sepak bola tingkat profesional. Mereka juga pernah merasakan kekosongan itu, tapi menemukan makna dari dalam diri.
Dari perspektif Islam yang saya pelajari, mengharapkan pengakuan manusia memang sia-sia. Kita diajarkan untuk ikhlas, mengharapkan ridha Allah semata. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib yang bersedekah secara diam-diam di malam hari—beliau tidak ingin manusia tahu, karena cukup Allah yang Maha Mengetahui. Atau Rabi'ah Al-Adawiyyah yang menyembah Allah hanya karena cinta, bukan mengharap surga atau pujian. Pujian manusia, jika dikejar, justru bisa mengurangi pahala amal kita.
Meski begitu, perasaan hampa ini tetap manusiawi. Saya sedang belajar kembali mencintai proses tanpa bergantung pada validasi luar. Mungkin dengan mengingat bahwa setiap tulisan, foto, atau repetisi di gym adalah amanah yang Allah titipkan—dan Dia Maha Melihat usaha kecil sekalipun. Semoga, perlahan, makna itu kembali utuh.